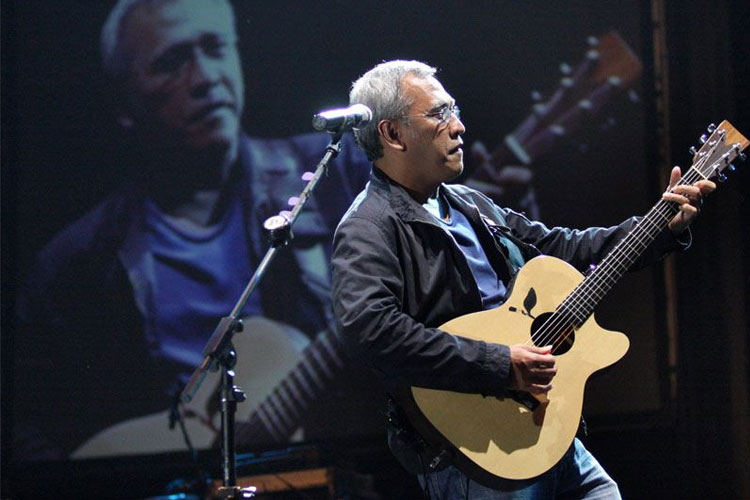TIMES MEDAN, JAKARTA – Ada sesuatu yang menarik sekaligus menyedihkan dari nasib Nadiem Makarim. Mantan Menristek Dikti era Presiden Jokowi itu. Eks CEO dan founder Gojek. Pendiri unicorn.
Anak muda yang pernah dielu-elukan dalam dunia start up teknologi. Sosok yang mampu menyulap ojek pangkalan menjadi ride hiling dengan jutaan anggota.
Kini, namanya masuk daftar tersangka kasus pengadaan Chromebook oleh Kejakgung.
Apakah ia korup? Belum tentu.
Apakah ia bisa lolos? Sulit.
Karena yang ia hadapi bukan hanya hukum, melainkan kultur. Kultur birokrasi yang jauh berbeda dengan dunia startup yang membesarkannya.
Leader Start up vs Leader Birokrasi
Nadiem datang dari dunia bisnis. Dunia di mana keputusan diambil cepat. Dunia di mana keberanian mengambil risiko dihargai. Dunia di mana “asal jalan” dianggap lebih penting daripada “asal sesuai prosedur”.
Itulah logika startup. Kultur dunia bisnis juga. Move fast, break things.
Tapi birokrasi negara tidak mengenal logika itu. Di sini, setiap rupiah harus ada dokumennya. Setiap keputusan harus ada dasar hukumnya. Setiap kebijakan harus siap diaudit oleh BPK, BPKP, Kejaksaan Agung, atau KPK.
Maka ketika ia menjadi menteri, benturan itu tak terhindarkan. Pengadaan Chromebook adalah contoh paling nyata.Program digitalisasi sekolah itu.
Ratusan ribu unit laptop harus segera diadakan dan disalurkan. Alasannya mulia: mengejar ketertinggalan pendidikan Indonesia.
Tapi jalan yang ditempuh terburu-buru. Vendor dipilih, kontrak diteken, barang datang.
Di startup, itu disebut efisien.
Namun di birokrasi, itu disebut maladministrasi. Kemudian di meja penyidik, itu bisa disebut tindak pidana korupsi.
Ruang Hukum Tipikor Negeriku
Hukum pidana kita memang unik.
UU Tipikor memberi ruang luas untuk menjerat pejabat, bahkan tanpa bukti ia memperkaya diri. Cukup ada kerugian negara. Cukup ada penyalahgunaan kewenangan.
Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor adalah jaring raksasa. Siapa pun bisa terseret di dalamnya. Termasuk pejabat yang hanya ingin berbuat baik.
Katakanlah ada fakta harga Chromebook lebih mahal dari standar pasar. Katakanlah vendor diuntungkan. Katakanlah dokumen tidak rapi.
Maka cukup: unsur delik terpenuhi.
Apalagi Nadiem, sebagai menteri, punya command responsibility.
Ia bisa bilang tidak tahu. Ia bisa bilang itu urusan teknis. Tapi hukum tetap berkata: ia yang bertanggung jawab. Dia KPA (kuasa pengguna anggaran).
Di sini kita melihat jebakan besar: criminalization of policy.
Kebijakan publik yang lahir dari niat baik bisa dipidana karena prosedur tak sempurna.
Bayangkan. Kalau semua kebijakan harus 100 persen sesuai aturan. Maka hasilnya lambat, tidak relevan, dan gagal menjawab tantangan zaman.
Kalau semua kebijakan dipercepat ala CEO, hasilnya cepat, tapi pejabat bisa terseret kasus Tipikor.
Paradoks kan!
Dimensi politik membuatnya makin rumit. Nadiem bukan kader partai. Ia tidak punya pasukan politik. Juga tidak ada ormas besar yang bisa jadi tameng.
Maka ketika kasus Chromebook meledak, ia sendirian. Tidak ada benteng. Tidak ada lobi kuat yang bisa melindungi.
Ia anak muda pintar, tapi ia bukan bagian dari ekosistem politik.
Dan di Indonesia, birokrasi adalah politik. Hukum juga politik.
Apakah ini berarti pejabat seperti Nadiem tidak boleh ada?
Tentu tidak. Kita tetap butuh orang-orang inovatif dari dunia bisnis. Tapi negara perlu menimbang ulang menyediakan “perisai regulasi” bagi mereka.
Harus ada safe harbor. Aturan yang membedakan mana kebijakan yang salah secara prosedural, mana korupsi yang nyata-nyata jahat.
Harus ada ruang bagi inovasi.
Karena tanpa itu, siapa pun yang berani berubah akan selalu terancam pidana.
Kasus Chromebook adalah pengingat. Bahwa reformasi birokrasi kita masih jauh tertinggal dari semangat zaman.
Bahwa regulasi kita lebih sibuk mengawasi dokumen daripada mengukur dampak kebijakan.
Bahwa hukum kita lebih mudah menghukum niat baik daripada membuktikan niat jahat.
Apakah Nadiem korban? Bisa iya, bisa tidak.
Tapi yang jelas, ia cermin. Cermin betapa jauhnya jarak antara kultur startup dan kultur birokrasi.
Inovasi vs Manipulasi, Administrasi vs Korupsi
Mari kita jujur, berapa banyak pejabat daerah yang bernasib sama?
Bupati, walikota, gubernur, menteri, banyak yang masuk penjara Tipikor bukan karena mereka menilep uang. Tapi karena mereka mereka menabrak prosedur.
Mereka ingin cepat membangun jembatan, pasar, atau rumah sakit. Tapi satu dokumen kurang tanda tangan. Satu harga di atas HPS. Maka vonis pun jatuh.
Kita menyebut mereka koruptor.
Padahal seringkali, mereka hanya pejabat yang tergesa.
Maaf, tulisan ini bukan pembelaan untuk Nadiem. Ini pengingat bagi kita semua. Bahwa hukum harus bisa membedakan: mana inovasi, mana manipulasi. Mana kesalahan administrasi, mana korupsi.
Kalau tidak, kita akan kehilangan pejabat-pejabat baik. Mereka takut berinovasi. Takut berkreasi. Lebih baik duduk diam, asal selamat.
Dan itu jauh lebih berbahaya bagi masa depan bangsa.
Namun penting dipertegas, jika memang terbukti korupsi hukum jangan setengah-setengah. Rampas hartanya, hukum mati pelakunya!
Nadiem adalah contoh. Ia datang dengan semangat membangun. Ia pergi dengan stigma tersangka.
Kita boleh kecewa padanya.
Tapi jangan lupa bercermin: masalahnya bukan hanya pada Nadiem, melainkan pada sistem yang membuat niat baik pun bisa jadi dosa. Wallahu a'lam bishshawab! (*)
Artikel ini sebelumnya sudah tayang di TIMES Indonesia dengan judul: Nadiem, Chromebook, dan Jebakan Tipikor
| Pewarta | : Khoirul Anwar |
| Editor | : Khoirul Anwar |